Oknum adalah istilah menyebalkan bagi pegiat demokrasi. Apa sih oknum itu? Satu atau sejumlah orang dalam satu institusi atau kelompok identitas tertentu yang ketahuan publik melakukan perbuatan tercela. Poin pentingnya ada di ketahuan publik melakukan perbuatan tercela. Kalau enggak ketahuan, ya batal jadi oknum. Namanya juga diksi humas.
Oh ya oknum punya nama panjang. Versi lengkapnya biasa disebut “oknum tidak bertanggung jawab”. Sudah oknum, tak bertanggung jawab pula.
Oknum adalah kata dengan cara pemakaian teramat munafik. Pasalnya, kata ini selalu dipakai untuk melokalisir masalah demi menyelamatkan so-called “nama baik” institusi/kelompok identitas, khususnya institusi yang emang problematis dan berulang kali tersandung kasus. Jadinya kalau ada bagian dari institusi atau kelompok ketahuan blangsak, ya itu si oknum doang, jangan dikait-kaitin sama karakter institusi atau kelompok dong!
Sebaliknya, kalau terkait anggota institusi yang berprestasi, kata oknum enggak pernah akan dipakai. Soalnya prestasi dia kan prestasi pimpinan juga, prestasi lembaga juga. Malesin banget kan? Persis kelakuan politisi Indonesia kalau udah hubungannya sama cabang olahraga berprestasi.
Pendek kata, manfaat oknum tuh melemahkan demokrasi semata. Satu, karena istilah ini anti-reformasi dan pro-status quo. Bagaimana mau mereformasi institusi, kalau di muka bumi ini persoalan sistemik enggak diakui, sebab semua-mua yang buruk adalah ulah individu.
Jadi meskipun berkali-kali polisi terungkap jadi bandar narkoba, berkali-kali pejabat setingkat menteri tertangkap akibat korupsi, berkali-kali pula jaksa ketahuan menerima suap; semua kasusnya selesai begitu aja sebagai dosa perseorangan. Tidak ada pembenahan sistem lembaga yang mendukung dosa-dosa itu bisa berulang terjadi. Mantap banget kan teori “oknum” ini?
Dua, oknum sepaket dengan konsep toxic tentang “nama baik”. Nama baik dianggap kayak protagonis novel-novel religi 2000-an, alias enggak pernah berbuat salah dan dosa. Kalau berbuat salah, nama baik otomatis rusak dan tak terpulihkan. Padahal kan enggak gitu. Kini kita sadar, masalah dan kesalahan pasti pernah menimpa siapa pun. Berbekal premis itu, menjaga nama baik berarti bagaimana cara institusi atau kelompok menangani suatu masalah. Apakah adil? Apakah bijak? Dan seterusnya.
Sayangnya, berkebalikan dengan popularitasnya, sejarah kata oknum ini masih misterius. Ada yang menyebutnya serapan dari kata Arab uqmum, artinya ‘orang’ atau ‘person’. Kata oknum juga kerap dipakai dalam gereja Katolik, untuk merujuk personifikasi Tuhan dalam diri Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Sampai sini netral dan baik-baik saja kan. So, what went wrong?
Peneliti Balai Bahasa Jawa Barat Asep Rahmat Hidayat menyebut kata oknum belum ada di Kamus Umum Bahasa Indonesia (1952) maupun Kamus Modern Bahasa Indonesia (1954). Lema ‘oknum’ baru muncul di edisi pertama Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pada 1988. Di KBBI edisi pertama itu, label negatif tersemat dengan didefinisikannya oknum sebagai ‘penyebut diri dalam agama Katolik; pribadi; orang seorang; perseorangan; dan orang atau anasir (dng arti yg kurang baik).’
Aku menghubungi sejarawan arsip Muhidin M. Dahlan untuk mencari tahu lebih dalam sejarah penggunaan kata oknum dalam media massa Tanah Air. Muhidin mengaku tak tahu pasti kapan dan siapa yang memopulerkannya. Hanya saja, ia tak pernah membaca kata ini tertulis di Harian Rakjat, koran yang menjadi studinya dan terbit sepanjang 1951-1965.
Menggabungkan pemaparan Muhidin dan Asep, aku mengasumsikan naiknya popularitas penggunaan istilah oknum untuk melindungi aib institusi terjadi antara 1965-1988. Kebetulan, rentang waktu itu punya panggilan akrab di Indonesia: Orde Baru.
Muhidin mengambil sebuah majalah yang terbit dari masa OrBa secara acak dan memperlihatkannya padaku. Sebuah artikel berjudul “Awas, Polisi Gadungan!” dari majalah Zaman tertanggal 26 Januari 1985. Di paragraf kedua, kata oknum sudah nyaman terselip. Kalimatnya begini:
“Ngomong tentang polisi sendiri tak akan ada habisnya. Terutama jika menyangkut citra Polri yang selalu menjadi bahan sorotan. Dari waktu ke waktu ABRI termuda ini belum juga mampu mengangkat harkatnya yang anjlok akibat ulah beberapa oknum Polri itu sendiri.”
Artikel ini membuktikan bahwa institusi Polri ternyata sudah memakai strategi melimpahkan kesalahan anggotanya secara personal, demi menjaga nama baik institusi, sejak 40 tahun lalu. Nuansa istilah oknum di artikel itu persis sama dengan masa sekarang, bahwa yang salah bukan lembaga sehingga tak ada yang perlu diubah dari lembaga. Muhidin menyebutnya sebagai “lokalisasi citra”.
“Tugas kata itu [oknum] adalah melokalisasi citrawi. Contoh, jika si tokoh A melakukan kejahatan. Untuk menyelamatkan institusi tertentu, misalnya, partai, cukup sebut oknum. Citra buruk itu dilokalisasi sebatas yang melakukan. Institusi selamat citranya. Itulah tugas kata ‘oknum’,” ujar arsiparis kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah tersebut.
Pergeseran oknum menjadi bermakna negatif di masa Orde Baru nyatanya sudah diatur. Menurut testimoni jurnalis senior Seno Gumira Ajidarma, semasa kepemimpinan Presiden Soeharto, para jurnalis diwajibkan mencantumkan kata oknum dalam produk jurnalistiknya saban kali ada anggota polisi dan ABRI yang ketahuan melakukan kejahatan. Aturan ini digalakkan pemerintah demi menekankan ke masyarakat bahwa pelaku kejahatan tidak mewakili lembaga yang ia ikuti.
“Pada masa orde baru, keteledoran [media] menyematkan kata ‘oknum’ dalam pemberitaan [buruk tentang militer] bisa mengundang peringatan,” tulis Seno di Majalah TEMPO.
Sayangnya, keruntuhan Orde Baru tidak lantas membuat warisan satu ini hilang. Oknum masih dan terus laris dipakai lembaga negara dan kelompok berkuasa untuk lari dari tanggung jawab.
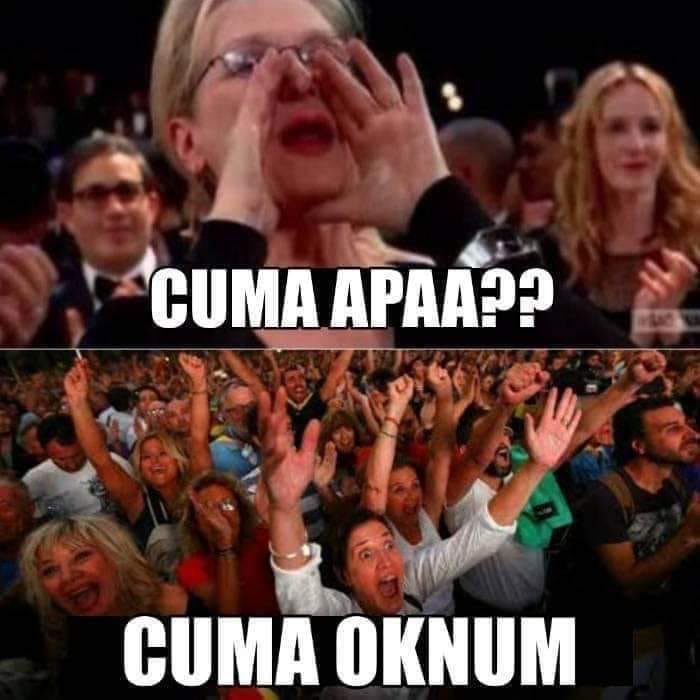
Parahnya, selain perluasan makna, terjadi pula perluasan penggunaan dari istilah ini. Bukan cuma TNI-Polri, institusi pemerintahan, atau parpol yang punya oknum. Kini pihak swasta juga cekatan mengambil manfaat dari kekuatan kata ini.
Kontroversi Holywings Juni 2022, misalnya. Ketika perusahaan merilis surat pernyataan merespons kampanye promosi miras bagi pemilik nama Muhammad dan Maria, mereka menulis, “Holywings Indonesia tentunya tidak memiliki maksud untuk menutup-nutupi kasus ini atau melindungi oknum yang terlibat.”
Republik ini hampir berusia 80 tahun, dua dasawarsa lagi jadi seabad. Saatnya demokrasi di negara kita semakin dewasa dengan membiasakan semua pihak, bahwa organisasi profesi tidak perlu terbebani bila anggotanya berbuat salah. Jurnalis bisa jadi pelaku kejahatan atau menerima suap. Demikian pula dokter, guru, polisi, arsitek, hingga tentara. Idealnya refleksi internal yang perlu digalakkan ketika aib perilaku muncul ke permukaan.
Masyarakat tidak bisa terus berpaling dari problem sistemik yang lebih penting diurai, seperti budaya korupsi atau penyalahgunaan wewenang, dibanding menjaga “nama baik institusi”. Sayangnya kekuatan pembelaan di balik kata oknum tampaknya masih begitu besar, begitu menggoda, begitu ampuh, demi menjaga harkat dan martabat penggunanya.
Setidaknya, banyak masalah sosial yang bisa dianalisis lebih terang bila kata oknum berhenti digunakan. Cocok lah menjadi resolusi kita bersama di HUT Republik Indonesia ke-77.














