Sejak beberapa tahun lalu, unggahan foto mahasiswi oleh berbagai akun ‘kampus cantik’ hadir di media sosial dan senantiasa mengundang kontroversi. Berbagai diskusi mengkritik fenomena ini —dari masalah komodifikasi dan komersialisasi konten oleh akun kampus cantik hingga pelanggaran privasi yang kerap terjadi. Misalnya, selama ini tak jarang akun-akun kampus cantik tersebut memuat foto tanpa persetujuan mahasiswi yang bersangkutan.
Tapi, bukannya menutup akun, di tengah badai kritik ini banyak dari mereka yang sekadar mengunci profil sehingga tak mudah diakses publik. Akun @uicantikid, misalnya, bersifat privat dan hingga kini punya lebih dari 220 ribu pengikut, serta banyak memanfaatkan tagar agar publik bisa menemukan sejumlah besar foto mahasiswi. Mereka tidak hilang, malah semakin tersembunyi dari pengawasan publik.
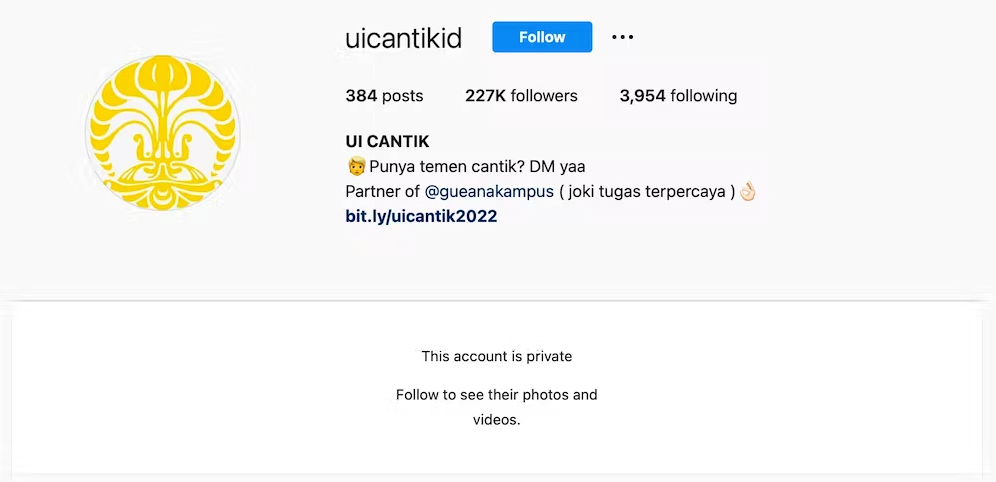
Dalam kacamata kami, akun-akun ini merupakan wujud praktik pendisiplinan tubuh perempuan yang membentuk sebuah hegemoni (kekuatan dominan) atas gender di lingkungan kampus.
Untuk mendalaminya, kami mengumpulkan data secara daring menggunakan perangkat lunak analisis NVivo (NCapture) untuk memahami diskursus yang terjadi pada beberapa akun kampus cantik. Kami juga melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa dan alumni perguruan tinggi negeri mengenai persepsi mereka terhadap akun-akun ini.
Meski tak dapat digunakan sebagai generalisasi fenomena kampus cantik, studi kami menemukan kentalnya budaya objektifikasi perempuan – baik dari mahasiswa laki-laki atau perempuan, atau bahkan kampus melalui pembiaran. Ini terjadi di lingkungan pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi ruang kritis.
Pendisiplinan tubuh perempuan lewat male gaze
Pakar teori film Laura Mulvey memperkenalkan konsep ‘male gaze’ untuk menggambarkan bagaimana laki-laki menggunakan sudut pandangnya untuk menciptakan wacana tentang perempuan dalam layar.
Wacana ini berupa citra yang dibuat untuk memenuhi kepuasan (pleasure) laki-laki dengan perempuan sebagai objek. Dalam male gaze ini, laki-laki mengikat perempuan sebagai simbol untuk memenuhi fantasi seksual mereka melalui berbagai citra yang menghapus kualitas perempuan, sehingga pandangan tentang perempuan seakan hanyalah tentang tubuhnya.
Di sini, akun kampus cantik memangkas perempuan menjadi ‘seonggok daging’. Tapi, pada saat yang sama, mereka juga melatih perempuan lain menormalisasi sudut pandang yang menempatkan mereka sendiri sebagai obyek pemuas seks.
Hal tersebut konsisten dengan data dalam studi ini. Baik laki-laki maupun perempuan memanfaatkan ruang yang disediakan akun kampus cantik untuk mereduksi keberadaan perempuan, sekaligus meminggirkan narasi tentang kemampuan akademik mereka.
Dulu kita menyalahkan media massa yang menyuguhkan konten-konten yang sesuai kepentingan mereka, termasuk konsep sex sells (seks itu menjual). Pada era digital, yang harapannya bisa mengangkat martabat perempuan, ternyata tak jauh berbeda dengan masa pra-digital.
Beragam komentar dari pengunjung laki-laki – seperti ‘cantiknya’, ‘sensual banget’, ‘trauma sama yang tepos lur’, ‘angan-angan yang terlalu tinggi buatku yang ga sampai 170cm’, ‘dah kek tante aja’, hingga ‘cantik sama seksi beda ga bosque?’ – menghiasi kolom komentar akun kampus cantik.
Sementara komentar dari pengunjung perempuan memperlihatkan bagaimana banyak dari mereka sendiri menormalisasi cara pandang tersebut. Tanpa sadar, perempuan menginternalisasi male gaze untuk memangkas keberadaan mahasiswi lain dengan berpartisipasi melalui komentar yang fokus pada penampilan.
Bagi saya, para perempuan ini seakan ‘meminjam mata laki-laki’ untuk mengobjektifikasi mahasiswi lain. Ini memperlihatkan bagaimana laki-laki tak hanya berhasil menggunakan cara pandang mereka untuk mendisiplinkan tubuh perempuan. Laki-laki turut melibatkan perempuan untuk menciptakan sistem agar pendisiplinan tubuh perempuan terus berjalan.
‘Rumah kenikmatan’ yang melanggengkan eksploitasi
Fenomena akun kampus cantik mengingatkan saya juga pada buku The Prostitution of Sexuality.
Sosiolog Kathleen Barry, sang penulis, menekankan segala praktik yang mereduksi perempuan sekadar jadi ‘seonggok daging’ adalah bentuk eksploitasi seksual. Akun kampus cantik, sebagai wacana maskulinitas, memajang wajah dan tubuh perempuan sebagai pusat perhatian di medsos, layaknya objek dalam etalase atau katalog.
Praktik tersebut menunjukkan adanya seksualisasi besar-besaran terhadap mahasiswi. Kondisi ini pun didorong karakter media sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi antar-partisipan, sehingga mereka sekaligus dapat membangun jejaring.
Pengunjung akun kampus cantik—yang mayoritasnya laki-laki—tak hanya menikmati atau memilah gambar tertentu, tapi juga dapat mencari, mengunduh, mengunggah, membandingkan, melakukan penilaian (love atau rating), dan memberi komentar. Berbagai aktivitas ini memudahkan pengunjung untuk semakin mengeksploitasi perempuan.
Wawancara kami dengan beberapa alumni kampus negeri memperlihatkan adanya beragam praktik kenikmatan laki-laki terkait foto mahasiswi dalam akun kampus cantik. Ini mulai dari sekadar kenikmatan melihat (visual pleasure) sampai kenikmatan seksual (sexual pleasure).
“Awalnya cuma buat liat-liat, lama-lama buat bahan coli,” ungkap salah satu responden.
Hasil wawancara ini konsisten dengan data yang kami tarik dari akun-akun tersebut. Kebanyakan komentar laki-laki yang kami kumpulkan mayoritas meminta nomor kontak WhatsApp, atau akun Instagram dan Twitter sang mahasiswi. Beberapa laki-laki nekat memberikan nomor kontak di kolom komentar dengan harapan mahasiswi yang dituju menghubungi nomor tersebut.
Komentar yang muncul menggambarkan bagaimana laki-laki mengkonstruksi seksualitas perempuan sebagai aset yang dapat diakses secara acak, gratis, dan semena-mena.
Simak saja komentar seperti ‘yang kek gini nih bikin pengen kuliah offline’, ‘dijadiin bini seer nih’, ‘gemesin dan bikin ah sudahlah’, hingga ‘berapa semalam?’.
Akun-akun kampus cantik ini berperan jadi suatu ‘rumah kenikmatan’ (house of pleasure) – tempat untuk memangkas dan memarginalisasi peran seksual, sosial, dan politik perempuan. Sementara, industri dan media sosial berperan sebagai fasilitator kekuasaan patriarki yang mememberikan ruang seluas-luasnya bagi kenikmatan laki-laki.
Institusi pendidikan, kekuasaan simbol, dan hegemoni
Studi kecil yang kami lakukan menunjukkan bagaimana masyarakat – tak terkecuali mahasiswa laki-laki dan perempuan – melanggengkan budaya pendisiplinan tubuh perempuan, bahkan di lingkungan pendidikan tinggi.
Padahal, ada banyak sarjana, terutama feminis, yang menaruh harapan besar pada lembaga pendidikan tinggi untuk memberdayakan civitasnya.
Pembiaran penggunaan logo institusi pendidikan oleh akun kampus cantik juga tidak dapat dianggap sepele. Di balik setiap logo perguruan tinggi tersemat wacana kekuasaan yang bisa masyarakat artikan sebagai ‘legitimasi’ atas praktik objektifikasi dan pelanggaran privasi terhadap perempuan.
Sayangnya, belum ada kampus yang menyatakan keberatan secara resmi. Harus diakui, seringkali langkah ini adalah sesuatu yang mereka anggap dilematis. Mereka kerap menimbang antara ‘menjaga reputasi nama baik lembaga’ yang sudah dikenal, dengan komitmen untuk melindungi mahasiswi dari pencurian data dan eksploitasi.
Mereka lupa bahwa pembiaran ini pada akhirnya akan menormalisasi eksploitasi seksualitas perempuan.
Praktik-praktik akun cantik juga akan menjadi sebuah ladang yang menyuburkan praktik peliyanan (othering) terhadap mahasiswi dan akademisi perempuan: apapun pencapaian mereka secara akademik, perempuan lahir hanya untuk menjadi objek seksual dan pemuas laki-laki.
Kampus seharusnya adalah lembaga yang yang memberi ruang sebesar-besarnya pada kemampuan akademis, bukan menyuburkan praktik yang memangkas keberadaan perempuan menjadi sebatas objek pemuas seksualitas laki-laki.
Billy Sarwono adalah Guru Besar bidang Ilmu Komunikasi dan Gender, FISIP Universitas Indonesia
Endah Triastuti peneliti sekaligus dosen di Universitas Indonesia terlibat dalam penelitian ini
Artikel ini pertama kali tayang di The Conversation Indonesia dengan lisensi Creative Commons. Baca artikel aslinya di sini.














